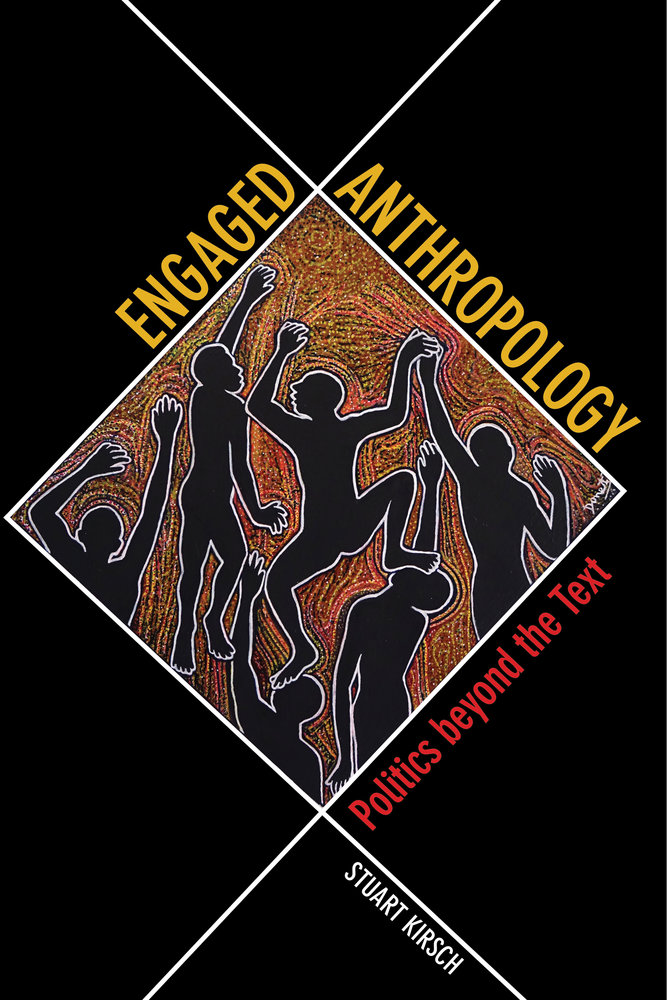JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ribuan pengungsi Papua yang menyeberang pada dekade 1980-an ke wilayah Papua Nugini dan bermukim di perbatasan dengan hidup yang pas-pasan, masih tetap menyimpan cita-cita merdeka, perjuangan yang dahulu menyebabkan mereka meninggalkan tanah asal mereka.
Hal ini terungkap dalam buku baru karya Profesor Antropologi Universitas Michigan, AS, Stuart Kirsch, berjudul Engaged Anthropology:Politics beyond Text, yang diterbitkan oleh University of California Press pada Maret lalu.
Subjek utama buku setebal 328 halaman ini sesungguhnya adalah hasil riset penulisnya terhadap penduduk asli di bagian hilir Sungai Ok Tedi, di perbatasan Papua Nugini dan Indonesia, yang mengadakan perlawanan terhadap pencemaran yang dilakukan sebuah perusahaan pertambangan di sana.
Namun, pada perjalanan risetnya, Kirsch bertemu dengan para pengungsi Papua di sekitar daerah itu, yang menyebabkannya terpacu untuk mendalami aspirasi mereka.
Dari hasil interaksi tersebut, ia menyediakan satu bagian dalam buku terbaru ini menceritakan pemikiran dan pengalamannya tentang kehidupan dan aspirasi pengungsi Papua di Papua Nugini. Pemikiran-pemikiran tersebut turut dijadikannya sebagai argumentasi membangun gagasan tentang Engaged Anthropology, sebuah genre baru antropologi yang tengah populer satu dekade belakangan ini.
Menurut Kirsch, sekitar 7.500 pengungsi Papua di PNG merupakan orang-orang yang memiliki aspirasi merdeka dan mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Mereka tetap menyimpan cita-cita tersebut walaupun menghadapi kehidupan yang sulit. Berkali-kali pemerintah PNG ingin merelokasi mereka dari perbatasan tetapi mereka menolak, karena hal itu dianggap akan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka.
Kirsch juga menentang pendapat berbagai ahli yang menganggap para pengungsi dari Papua ini menyeberang ke PNG demi alasan mencari penghidupan yang lebih baik.
Menurut Kirsch, mereka adalah pengungsi politis, dan para pengungsi tersebut tanpa kecuali mengidentifikasi diri mereka dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan mengemukakan bahwa tujuan mereka adalah kemerdekaan Papua.
“Saya prihatin dengan kegagalan pengamat luar untuk mengambil perspektif pengungsi dan tujuan mereka dalam laporan mereka untuk mengambarkan situasi di perbatasan Papua Nugini,” tulis peraih gelar Ph.D dari University of Pennsylvania dan pernah mengajar Arctic University of Norway itu.
Selain untuk meluruskan pendapat para ahli yang keliru, penegasan bahwa mereka adalah pengungsi politik dan bukan pengungsi tradisional yang ingin mencari kehidupan lebih baik, menurut Kirsch, perlu dilakukan untuk menggugah simpati rakyat PNG kepada mereka.
Apalagi, lanjut Kirsch, bila status mereka sebagai pengungsi dinegasikan dan mereka hanya dianggap sebagai penyeberang, konsekuensinya adalah PNG sebagai negara akan bisa mengabaikan tanggung jawab internasionalnya terhadap mereka, termasuk kemungkinan tidak memberikan perlindungan terhadap pemulangan (repatriasi) paksa.
Menurut Kirsch –yang dengan sadar memilih menjadi antropolog yang turut berjuang dengan berbagai gerakan penduduk asli di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara Kepulauan Pasifik dan di Amazon — klaim bahwa mereka bukan pengungsi politik juga akan “mengabaikan pengorbanan mereka dan mengaburkan motivasi dan tujuan politik mereka.”
Dalam buku ini, Kirsch juga menceritakan bahwa para pengungsi tersebut pernah berusaha untuk direlokasi pada tahun 1988. Tetapi mereka menolak karena mereka menganggap hal itu akan menjauhkan mereka dari saudara-suadara mereka yang berada di Papua, selain karena mereka masih terikat dengan unit OPM di perbatasan.
Penolakan itu juga terjadi dengan alasan hal itu akan meningkatkan ketergantungan mereka kepada PBB, yang mereka kritik karena ‘menghianati’ mereka dan berpihak pada Indonesia pada tahun 1963 dan tahun 1969.
“Meskipun mereka (para pengungsi, Red) gagal melakukan perubahan politik atau bahkan memprovokasi reformasi substantif di Papua, lebih dari 7500 pengungsi yang hidup di perbatasan tetap bertahan meskipun mereka menjalani hidup yang keras di pengungsian, mayoritas mereka berkomitmen kepada tujuan politik awal,” tulis Kirsch.
Cita-Cita Merdeka Penggerak Hidup
Apa yang dikemukakan oleh Kirsch dalam buku baru ini, mirip dengan yang dikisahkan oleh Emma Kluge, seorang perempuan muda asal Australia, yang sedang menyelesaikan studi S-3-nya dalam bidang Sejarah di University of Sydney.
Kluge melaksanakan riset dalam rangka disertasinya di tempat pengungsian orang Papua di PNG awal tahun ini dan ia menemukan bahwa passion untuk mencapai kemerdekaan pada orang-orang Papua di PNG sangat kuat. Ia bahkan menilai cita-cita merdeka menjadi pendorong di balik apa pun yang mereka kerjakan.
Seperti dapat dibaca dari blog pribadinya, Emma Kluge Life and Thoughts of a Ph.D. Student, awal Februari lalu ia terbang ke Papua Nugini demi keperluan penelitiannya. Risetnya mengambil topik tentang perjuangan kemerdekaan rakyat Papua di tahun 1960-an hingga 1970-an.
Selama tiga pekan lebih di sana, ia mewawancarai mereka yaitu orang-orang Papua yang dulu melarikan diri ke PNG pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Dan Emma Kluge menilai betapa passion untuk merdeka itu demikian kuatnya.
“Salah satu tema yang muncul berulang kali di seluruh wawancara adalah bagaimana perjuangan untuk kemerdekaan Papua dan harapan untuk masa depan yang lebih baik membingkai seluruh cara mereka mendekati kehidupan dan memberikan tujuan untuk kehidupan sehari-hari mereka,” tulis Emma Kluge.
“Baik tua maupun muda, mereka berbicara tentang bagaimana terlepas dari perjuangan dan kesulitan, mereka bertekun dan mendedikasikan diri mereka untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia – pendidikan, sumber daya, pekerjaan – untuk membantu mengembangkan diri mereka sendiri, untuk mendukung komunitas mereka dan untuk memastikan masa depan yang terbaik bagi Papua,” demikian ia menulis di blognya.
Lebih jauh, Kluge mengatakan, “Ketidakadilan yang mereka saksikan terjadi di Papua, diskriminasi dan penganiayaan, memandu mereka untuk mengerahkan apa pun yang mereka miliki di Papua Nugini, seterbatas apa pun itu.”
Kepada suarapapua.com, Emma Kluge mengungkapkan ketertarikannya pada sejarah Papua dan melakukan riset di bidang ini ialah setelah mempelajari arsip-arsip di Australia tentang Papua Nugini. “Saya menemukan pengungsi Papua dalam arsip pemerintah saya di sini dan kemudian minat saya pada gerakan kemerdekaan tumbuh dari sana,” kata Kluge.
Meskipun demikian, Kluge menahan diri untuk memberikan pendapat tentang aspirasi merdeka para pengungsi di Papua tersebut. “Saya sejarawan jadi saya tidak bisa memberikan banyak jawaban untuk itu. Saya akan merekomendasikan karya Camellia Webb-Gannon – ia menulis tentang gerakan kemerdekaan dari masa lalu ke masa kini dan memiliki komentar tentang kepemimpinan dan penyebarannya di seluruh dunia,” kata dia.
Antropologi yang Terlibat
Dalam buku Engaged Anthropology ini, Kirsch juga menceritakan pengalaman pribadi yang menjadi momentum dirinya terlibat dalam membantu perjuangan orang-orang Papua yang beraspirasi merdeka.
Kirsch mengatakan ia turut dalam sebuah ritual inisiasi bersama orang-orang Papua yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Kobarara, yang berasal dari desa Ninati di Papua tetapi sejak 1984 hidup di tempat penampungan pengungsi di PNG.
Seusai ritual itu, Kirsch berbincang-bincang dengan mereka. Lalu ia ditanyakan sebuah pertanyaan yang membuat dirinya merenung: untuk apa ia melakukan riset, apakah hasil risetnya itu akan dipergunakan untuk membantu perjuangan mereka mencapai kemerdekaan atau justru akan dipakai untuk membantu Indonesia?
Hal itu memicu Kirsch untuk mencari cara membantu mereka, walaupun pada awalnya ia masih bingung untuk berkontribusi dalam hal apa. Tetapi setelah perjuangan perlawanan bersenjata para pejuang Papua Merdeka beralih menjadi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Kirsch menemukan cara untuk membantu. Ia terlibat dalam berbagai advokasi, termasuk bersama tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octo Mote.
Dalam buku terbaru ini, Kirsch menjawab pertanyaan apakah Antropologi dapat berkontribusi lebih banyak daripada sekadar teks-teksnya? Kirsch menunjukkan bagaimana Antropologi dapat — dan mengapa ia harus lebih terlibat dengan masalah-masalah dunia. Dalam buku ini ia mencurahkan pengalamannya bekerja dengan penduduk asli yang berjuang untuk melestarikan lingkungan mereka, memperjuangkan hak atas tanah, dan kedaulatan politik. Lewat buku ini ia hanya hanya mempromosikan cara baru dalam mempraktikkan Antropologi, tetapi juga mengartikulasikan alasan baru mengapa Antropologi itu penting.
Pewarta: Wim Geissler