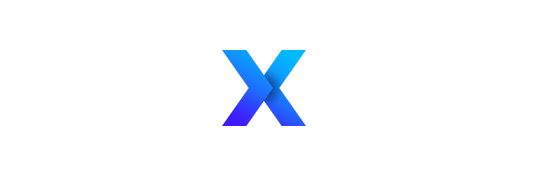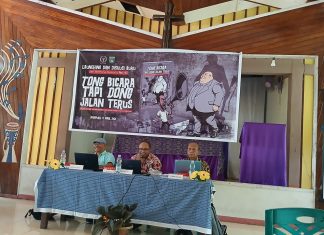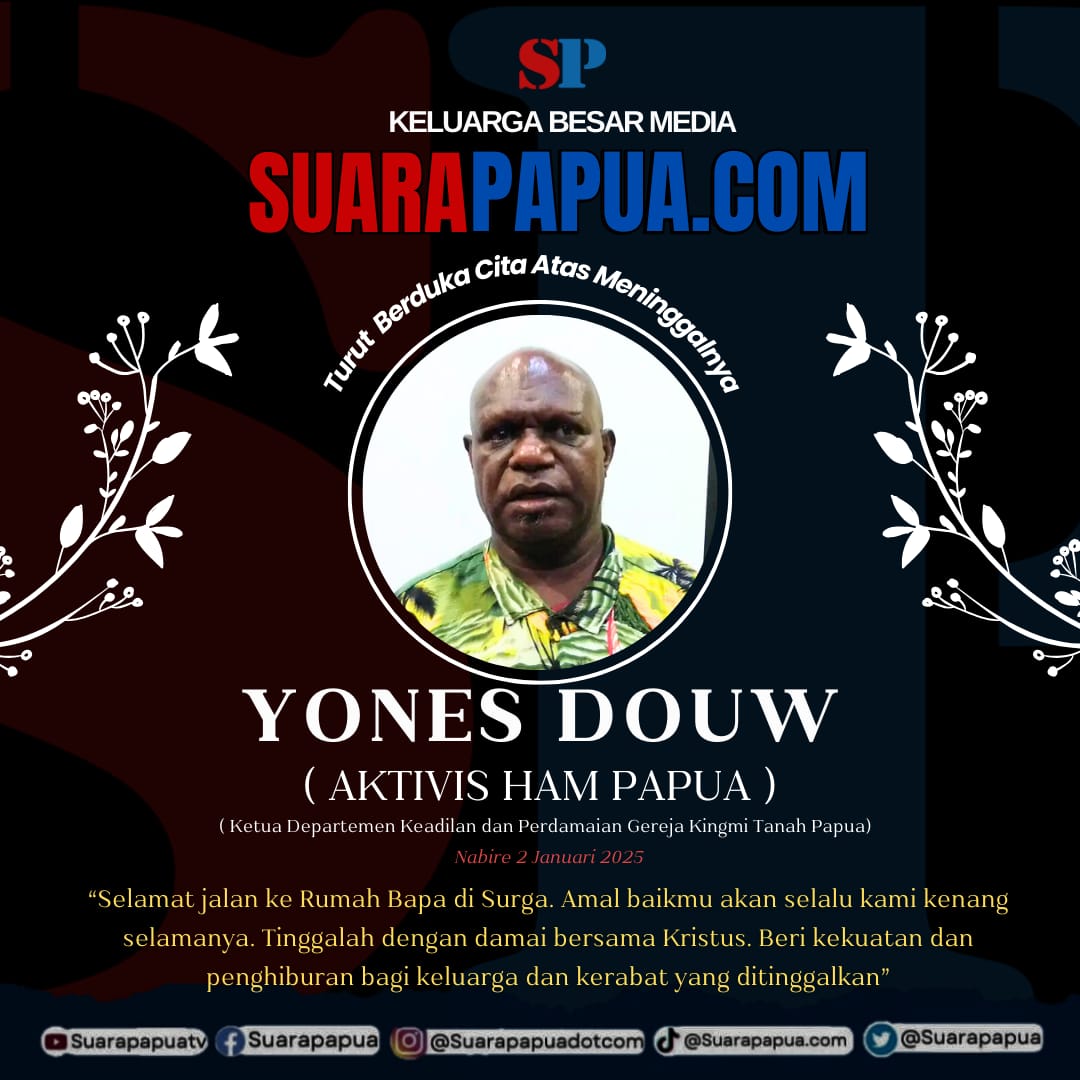Oleh: Melkior N. N. Sitokdana*
*) Akademisi Asli Papua di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah
Tanah Papua diibaratkan seperti permata indah dan berharga yang terletak di tengah-tengah gurun pasir yang tandus. Kalimat ibarat ini menggambarkan paradoks antara kekayaan alam Papua yang melimpah di satu sisi dan sisi yang lain kondisi orang asli Papua (OAP) yang semakin terpinggirkan dan termarginal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menetapkan marginalisasi sebagai salah satu dari empat akar masalah Papua. Persoalan marginalisasi tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan para investor beberapa dekade ini, seperti pemberlakukan Undang-undang Otonomi Khusus Papua sejak tahun 2001, berbagai produk hukum berupa keputusan presiden/peraturan pemerintah untuk percepatan pembangunan Papua, proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), perkebunan kelapa sawit seluas 240 ribu hektare di seluruh Tanah Papua (data tahun 2021), divestasi 51,2, persen saham PT Freeport Indonesia, kilang gas di kabupaten Teluk Bintuni, pemekaran kabupaten/kota sejak tahun 2002 hingga saat ini menjadi 6 provinsi di Tanah Papua, pembangunan infrastruktur dan gedung secara masif beserta industri ikutan lainnya yang diharapkan memberikan ruang seluas-luasnya bagi OAP untuk menjadi tuan di negeri sendiri.
Tetapi dibalik itu masih kontras dengan kehidupan orang Papua yang kian termarginalkan di negerinya sendiri. Tentu saja hal ini bukan tanpa penyebabnya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya marginalisasi.
Faktor utama yang berkontribusi terhadap marginalisasi orang asli Papua adalah sebagai berikut:
- Ketimpangan sosial dan politik
- Diskriminasi dan stigmatisasi
- Ketidaksetaraan ekonomi
- Kekerasan dan konflik
- Eksploitasi sumber daya alam (SDA)
- Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan
Ketimpangan Sosial dan Politik
Ini salah satu faktor penting OAP termarginal. Data demografi menunjukkan gap yang cukup jauh antara penduduk asli dengan non-Papua karena gelombang migrasi secara besar-besar ke Tanah Papua dengan tujuan pemerataan penduduk, peningkatan produksi perusahaan, keamanan negara dan peluang kerja.
Program transmigrasi di Papua mulai ditetapkan dengan adanya kebijakan Presiden Soeharto melalui Keppres nomor 7 tahun 1978 tentang penentuan provinsi Irian Jaya sebagai salah satu daerah provinsi di Indonesia. Kala itu, Papua dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah penerima transmigran tertinggi pada tahun 1978.
Pasca reformasi dan adanya pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Papua, tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Pemekaran wilayah seperti magnet yang menarik minat para penduduk luar yang memiliki kemampuan dan keterampilan tinggi berdatangan untuk menguasai ruang-ruang sosial, ekonomi dan politik yang tersedia, sementara OAP yang sudah dispesialkan dengan UU Otsus malah semakin termarginal.
Gejala marginalisasi dalam bidang politik bisa kita lihat dari perolehan kursi DPRD kabupaten/kota di Tanah Papua periode 2019-2024, dimana beberapa daerah Non-OAP mendominasi lebih dari 50% kursi DPRD, seperti di kota Jayapura 68%, kabupaten Jayapura 72%, kabupaten Sarmi 65%, kabupaten Boven Digoel 80%, kabupaten Merauke 90%, kabupaten Keerom 70%, kabupaten Sorong 85%, kabupaten Fakfak 60%, kabupaten Raja Ampat 55%, kota Sorong 80%, dan kabupaten Teluk Wondama 56%.
Selain politik, proporsi ASN beserta jabatannya di birokrasi pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih didominasi Non-OAP, sehingga pelayanan publik yang afirmatif bagi OAP seringkali tidak tepat sasaran karena sense of belonging terhadap OAP masih rendah.
Diskriminasi dan Stigmatisasi
Fakta bahwa OAP sering mengalami diskriminasi dan stigmatisasi di tingkat sosial dan institusional. Stereotip negatif dan prasangka terhadap mereka seringkali membatasi akses mereka terhadap kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Stigma bodoh dan tidak mampu, terbelakang, pemalas, etos kerja rendah, kasar, tukang onar, tidak dengar-dengaran, separatis, dan stigma lainnya yang disematkan kepada OAP membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan yang layak dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.
Contoh berbagai kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap orang asli Papua tidak pernah diusut secara adil, berbagai tes ketenagakerjaan dan akses pendidikan (CPNS, karyawan, TNI-Polri, perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, dan lain-lain) masih belum berpihak kepada orang asli Papua. Mahasiswa Papua yang studi di luar Tanah Papua seringkali diperlakukan rasis, dan masih banyak lagi contoh kasus perlakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap OAP.
Ketidaksetaraan Ekonomi
Tingkat pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Orang Asli Papua seringkali terbatas dalam mengakses peluang ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi OAP.
Akses lapangan pekerjaan non-pemerintahan masih sulit, misalnya dalam industri pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, penerbangan, jasa transportasi, perhotelan, restoran, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan lain-lain masih didominasi oleh Non-OAP.
Lazimnya OAP sulit mendapat pekerjaan, sehingga mereka harus menunggu formasi CPNS bertahun-tahun, namun ujung-ujungnya banyak dikecewakan karena kalah saing dengan Non-OAP.
Contoh lain, mama-mama Papua menjadi tumpuan ekonomi keluarga dari hasil jualan pinang, sayur-mayur, bumbu-bumbu, umbi-umbian, ikan, sagu dan daging di emperan toko dan pasar beralaskan karung bekas dan beratap langit. Sebuah paradoks yang belum terpecahkan selama 20 tahun lebih Otsus Papua diberlakukan di Tanah Papua.
Kekerasan dan Konflik
Papua telah menjadi saksi berbagai konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan TNI-Polri sejak tahun 1960-an sampai saat ini belum berakhir. Kekerasan dan konflik bersenjata memperburuk situasi sosial dan ekonomi di Tanah Papua, mengakibatkan ketidakstabilan, trauma, dan pembatasan akses terhadap layanan dasar yang layak bagi masyarakat asli Papua, terutama daerah konflik seperti di kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, dan Maybrat.
Eksploitasi SDA
Eksploitasi sumber daya alam di Papua, seperti pertambangan dan perkebunan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak tanah dan kebutuhan masyarakat asli Papua. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, kehilangan mata pencaharian tradisional, dan konflik atas hak tanah masyarakat adat.
Berbagai perusahaan masuk eksploitasi alam Papua seperti PT Freeport, proyek MIFEE, perusahaan kepala sawit, kilang gas di kabupaten Teluk Bintuni, perusahaan perikanan dan sebagainya, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat asli Papua. Faktanya sampai saat ini IPM masih sangat rendah dan kemiskinan masih tinggi.
Ketidaksetaraan Akses Terhadap Pendidikan
Selama ini OAP sering menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Faktor-faktor seperti kurangnya sekolah, guru yang terlatih, kurikulum yang relevan dengan budaya lokal, serta infrastruktur pendidikan yang buruk dapat membatasi akses mereka ke pendidikan yang layak. Pada akhirnya banyak generasi muda Papua yang sudah menyelesaikan perguruan tinggi, tetapi belum mampu memaksimalkan peluang kerja yang tersedia karena kualitas SDM yang masih sangat rendah, sehingga peluang tersebut diisi oleh para pendatang yang sudah siap dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai.
Penanganan masalah marginalisasi OAP sebagaimana diuraikan dalam artikel ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta dialog antarkelompok yang inklusif merupakan beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi marginalisasi dan meningkatkan kesejahteraan OAP di Tanah Papua.
Semua hal tersebut harus diproteksi dengan regulasi turunan dari UU Otsus Papua berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), misalnya mengatur tentang ketenagakerjaan OAP, kependudukan OAP, partai politik lokal Papua, pendidikan kontekstual Papua, pengelolaan SDA berbasis masyarakat adat, dan lain-lain supaya cita-cita Otsus Papua yakni melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi kepastian hukum, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, dapat terwujud. (*)