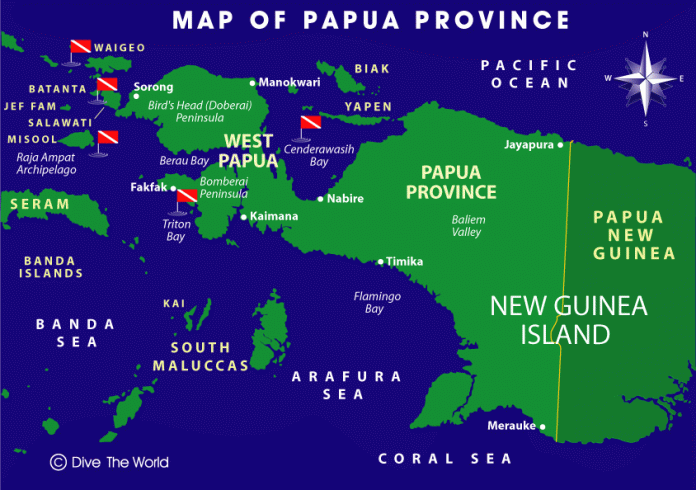HARI ini genap 73 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) eksis bertengger di Bumi Pertiwi. Hari bersejarah, hari kemerdekaan. Rakyat Sabang-Merauke merayakannya dengan berbagai acara seremonial rutin tahunan. Upacara bendera Merah Putih tentu salah satunya.
Bagi orang Papua, pertanyaan reflektif yang selalu terulang tiap tahun adalah: apakah kitorang sudah merdeka dalam bingkai NKRI?
Merayakan 17 Agustus tentu sudah bukan hal baru sebagai bagian dari warga negara yang baik. Jikapun banyak juga yang tidak terlibat, tentu saja ada alasan logis. Sejarah politik dan sejarah kelam bangsa adalah alasan inti!
Tidak karena marah terhadap beberapa kejadian jelang hari kemerdekaan, penangkapan mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, penangkapan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) Jayapura, dan kejadian lain beberapa hari sebelumnya. Sama sekali tidak karena itu.
Orang West Papua tidak merasa penting dengan momentum 17 Agustus pada setiap tahun karena ada sejarah bangsa. Masih menganggap bukan bagian dari NKRI.
Bila disimak lebih mendalam, orang West Papua sejatinya bukan apatis dengan hari bersejarah negara ini. Bukan tidak mau merayakan. Tetapi, sebenarnya negara melalui aparatusnya menjadikan rakyat West Papua bukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Orang Papua seperti “tamu” di NKRI.
Ada banyak fakta kalau kita beberkan. Satu contoh dalam banyak kebijakan negara, orang Papua acapkali dipaksakan harus menjadi WNI. Mengibarkan sehelai Merah Putih di depan rumah atau di halaman rumah, adalah salah satu cara pemaksaan dimaksud. Padahal, seharusnya tidak perlu ada pemaksaan. Seperti kejadian di Surabaya, mahasiswa Papua dipaksa tanam tiang dan kibarkan Merah Putih. Bukankah itu pemaksaan?
Selama pendekatan demikian terus berlanjut setiap tahun, mata dunia akan terbuka lebar. Banyak pandangan miring kian deras mengarah ke nusantara ini. Eksistensi orang Papua di NKRI akan disoroti dalam banyak forum resmi di fora internasional.
Apalagi pola pendekatan, kebijakan dan program ditambah realisasi di lapangan, selalu bertolakbelakang dengan panjangnya daftar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua. Terutama di era Otonomi Khusus (Otsus), belum termasuk selama masa represif dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), dan jauh sebelum itu adalah semenjak dimulainya proses aneksasi West Papua ke NKRI.
Sejak itu pula sejarah kekerasan negara di tanah emas ini tidak berujung. Tidak satupun berhasil ditangani. Semua hilang ditelan bumi pertiwi. Kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014, misalnya, yang diyakini akan diproses, hingga kini tak ada kabar lagi. Jakarta bungkam seribu bahasa.
Padahal, kasus berdarah ini sempat menggema hingga ke dunia internasional. Sayangnya, tiada respon dari negara. Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali ke Papua, tak satu katapun tentang kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.
Di kota apalagi di pinggiran, pelosok kampung, rintihan anak negeri terus berlanjut. Kecewa, sakit hati, bahkan hampir gila dengan tingkah negara memperlakukan warganya. Orang West Papua ada di lingkaran ini. Sudah tidak percaya negara bersama aparatusnya!
Fakta banyak terjadi kasus kekerasan negara sudah berawal sejak pencaplokan West Papua. Dari deretan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, kekerasan negara paling banyak terjadi dan sarat makna politis. Anak negeri bertumbangan demi dan atas nama keutuhan negara. Demi integrasi bangsa. Demi nasionalisme Merah Putih. Lebih dari itu adalah semua dilakukan dalam rangka upaya menggenggam erat “dapur dunia” tetap milik Indonesia.
Inilah fakta kelam selama setengah abad. Jikapun ada berbagai program pembangunan plus slogan manis yang selalu digembar-gemborkan, faktanya tak lantas mengakhiri kebiadaban negara terhadap rakyatnya di tanah emas. Justru sebaliknya, dalam praktiknya, rakyat Papua Barat diperlakukan berbeda. Perlakuan berbeda oleh negara sangat sadis dengan aksi intimidasi, penyiksaan, pembunuhan, penembakan, yang menjurus pada penghabisan ras (genosida).
Indonesia sendiri selalu akui Pancasila adalah dasar negara yang diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai persatuan termaktub didalamnya sebagai nilai adigung kebangsaan yang terus menerus diperjuangkan selama ini.
Faktanya, persatuan yang telah diperjuangkan itu telah pudar dalam diri bangsa Indonesia karena banyak diwarnai dengan tindakan kekerasan. Itu artinya, Pancasila sebagai dasar negara hanya sebagai alat bagi pemerintah untuk menindas masyarakat.
Kalau begitu, persatuan dan kesatuan yang merupakan jalan menuju kemerdekaan sejati, justru dibalik sebagai jalan penindasan dan penghancuran terhadap harkat dan martabat masyarakat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tetapi satu” sudah tidak ada makna. Perbedaan yang menjadi satu telah dipecah-pecahkan dan akhirnya perbedaan itu tampak dalam setiap komponen hingga menjurus pecahnya bangsa-negara.
Ernest Renan melalui tulisannya yang sangat terkenal “What is Nation?”, menegaskan makna nation adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun pengorbanan. Nah, ketika melihat berbagai tindakan kekerasan, dimanakah Pancasila sebagai dasar negara? Dimanakah makna Bhinneka Tunggal Ika? Semuanya tiada makna. Konsep dan semboyan kosong!
Terbukti pendekatan militeristik telah menewaskan banyak warga sipil. Orang Papua yang berdomisili di kawasan pegunungan, pedalaman dan daerah terisolir, tidak luput dari serangan militer. Meski negara melalui aparatus dan kaki-tangan selalu berusaha menutup rapat fakta pertumpahan darah, tanah emas ini mencatat sejarah kelam begitu tragis dirasakan puluhan tahun lamanya.
Derita batin orang Papua sulit diobati. Tidak saja pada masa DOM, kondisi memprihatinkan justru masih berlanjut di era Otonomi Khusus (Otsus). Parahnya lagi, kebijakan Otsus tidak sama sekali mengakhiri konflik berdarah dan kekerasan negara.
Pemberlakuan UU Otsus dianggap sebagai gula-gula politik, bahkan tak ubahnya sebuah dongeng siang yang dikisahkan pemerintah kepada OAP. “Otsus gagal total” adalah kesimpulan akhir rakyat West Papua.
Otsus jadi jembatan emas masuknya paket derita berkepanjangan. Alih-alih pembangunan untuk bisa bikin senyum rakyat, rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM di seluruh West Papua makin subur. Kasus Wasior (2003) — menewaskan 4 orang, dan Kasus Wamena (2005) — korban 9 orang, adalah dua bukti dari banyaknya fakta tragis di era Otsus. Itu bukti Otsus Berdarah di Tanah Papua.
Wacana dialog Jakarta-Papua sulit dapat titik temu. Masing-masing pihak tetap pada pendirian. Sementara, membiarkan kondisi hari ini terus berlanjut sama halnya membuka lebar jalan bagi OAP menuju liang kubur besar di NKRI. ***